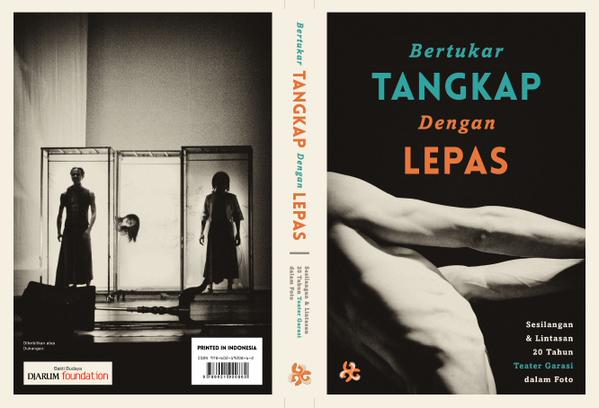Menonton Buku: Peristiwa
Pembekuan 20 Tahun Teater Garasi
Oleh: Shohifur Ridho Ilahi
Buku adalah peristiwa pembekuan ingatan dan hal-hal di
sekitar masa lalu. Buku melampaui kerja-kerja dokumentasi. Ia hadir untuk
menjadi peristiwa yang lain bagi dirinya dan pembaca, suatu peristiwa pemaknaan
atas sejarah dengan referensi konteks ruang-waktu yang tengah berlangsung di
masa kini.
Melalui buku Bertukar Tangkap
dengan Lepas; Sesilangan dan Lintasan 20 Tahun Teater Garasi dalam Foto dan Bertukar Tangkap dengan Lepas; Sesilangan
dan Lintasan 20 Tahun Teater Garasi dalam Esai, peristiwa pembekuan
berlangsung. Halaman demi halaman buku membangkitkan situasi yang dulu,
memproyeksikan ‘masa lalu’ yang ‘di situ’ ke dalam aku-pembaca yang ‘kini’ dan
‘di sini’. Dua buku ini berdiri sopan di samping gelaran Karnaval 20 tahun
Teater Garasi pada Desember 2013 lalu, yang juga
terdapat peristiwa pembekuan: pameran kostum, properti, poster, naskah dan
benda-benda lainnya yang dianggap representatif. Rekaman pentas dalam format video,
pementaskan ulang (reenactment) dan penciptaan
ulang (recreation) yang dilakukan
oleh beberapa aktor muda Yogyakarta atas sebagian pertunjukan Teater Garasi
selama dua dasawarsa ini juga mengambil peran dalam upaya penghadiran.
Katalog
Pada buku pertama, kita bersihadap dengan kumpulan foto 20
tahun perjalanan Teater Garasi. Foto-foto yang dikurasi Budi N.D Dharmawan dari
43 ribu foto itu semacam upaya pengisahan dirinya ke dalam sebuah periode
masyarakat di mana foto-foto kurang dipandang sebagai sebuah kesadaran untuk
merawat ingatan, namun tak lebih dari presentasi ketubuhan ke hadapan publik
melalui benda-benda teknologi. Dalam konteks yang demikian, buku ini sudah
menunjukkan sisi performatifitas dan mekanisme teatrikalnya.
Foto-foto dalam buku ini dibagi dalam empat bagian,
segendang-sepenarian dengan empat periode yang dirumuskan oleh Teater Garasi
sendiri: periode 1: 1993-1998;
Pertunjukan Mahasiswa di Akhir Sebuah Era: Awal yang Menentukan Watak,
periode 2: 1999-2001: Transisi;
Merumuskan Ulang Pertanyaan-pertanyaan: Apropriasi dan Adaptasi, periode 3:
2002-2007; Menjelajah Dunia dari Rumah
Kaca: Laboratorium Penciptaan Teater, periode 4: 2008-2013; Keluar ke Jalan, Memasuki Kenyataan di Ruang-ruang Antara:
Menuju Garasi Performance Institute.
Saya cenderung melihat foto sebagai katalog sejarah dan
paket wisata ke masa lalu. Mengunjungi pribadi-pribadi yang tampak asing,
melihat peristiwa sedalam-sedetailnya, menikmati keintiman sebaik-sejujurnya.
Kecenderungan ini membawa saya pada asumsi bahwa ketimbang foto-foto dua
periode terakhir yang mungkin dipotret oleh seorang fotografer profesional
dengan kamera mutakhir, foto-foto amatir pada dua periode awal tersebut justru
jauh lebih berkisah, sebab pada dirinya sudah menunjukkan kondisinya: foto-foto
itu dibuat dengan teknik alakadarnya, dengan kondisi gambar yang amatiran, tapi
justru dengan itulah sebuah zaman direpresentasikan: menunjukkan secara
telanjang kisah dan sudut pandangnya.
Menikmati foto menjadi pengalaman visual tersendiri yang berbeda dengan pengalaman (audio-)visual
dalam menonton pertunjukan di panggung. Hubungan sapasial dan temporal
menemukan konteksnya ketika terjadi pergeseran dari ‘peristiwa menonton’ gambar
yang bergerak (panggung) ke ‘peristiwa melihat’ gambar yang beku (foto). Namun
karena foto adalah jenis peristiwa yang kedua, maka tulisan Farah Wardani dalam
buku yang kedua tentang pengalamannya menonton sejumlah pertunjukan Teater
Garasi melalui arsip video menjadi relevan: sejauh mana sebuah arsip (foto)
bisa menghadirkan kembali momen tersebut, atau sejauh mana momen itu tereduksi
dalam arsip?
Trilogi
Teater sebagai alternatif alat baca kenyataan sosial dan
keterlibatan secara dialektis dengan publik adalah paradigma yang
dikumandangkan Teater Garasi. Paradigma ini mendapat porsi yang baik pada
penciptaan pasca 98, di mana basis dan titik tolak penciptaannya bukan pada
naskah yang sudah ada, tetapi riset dan investigasi langsung atas isu sosial yang
terjadi di masyarakat. Karya-karya yang pola kerjanya demikian adalah: serial Waktu Batu 1-3 (2001-2004), Je.ja.l.an (2008) dan Tubuh Ketiga (2010).
Melalui pertunjukan itu, beragam persoalan masyarakat
dikuliti, ditunjukkan darah-daging-penyakitnya. Beragam tema dijelajahi,
merentang dari yang tradisional sampai kontemporer, dari mitos-mitos Jawa
sampai identitas masyarakat poskolonial, dari wacana urban sampai politik internasional,
dari isu kekerasan sampai gender, dan seterus-sebagainya.
Paradigma dan pola kerja yang dipraktikkan Teater Garasi disempurnakan
dengan pilihan artistiknya yang segar. Tema-tema tersebut dipertemukan, wacana
dan gagasan diduduk-beriringkan, simbol-simbol dimuncul-tampakkan, konteks
ruang waktu diruntuhkan, masa lalu dan kini dileburkan. Pada pertunjukan Je.ja.l.an dan Tubuh Ketiga posisi penonton dan pemain sama-sama aktif, jarak
ditiadakan, pembauran dilangsungkan, pelbagai disiplin seni dicairkan. Sifat
pertunjukan semacam ini mengisyaratkan keterbukaan. Partisipasi penonton adalah
kata lain dari gagasan emansipasi dan kebebasan.
Menonton karya Teater Garasi yang disebut di atas seperti
membaca esai dalam wujud visual, menyuntuki data dalam rupa benda-benda, mengkhidmati
wacana dalam tubuh sastra. Citraan berlapis-lapis, intelektualisme meraung-raung,
kekacauan panggung mendapat momennya dalam masyarakat hari ini di mana idiologi
kontemporer melapangkan benturan dan kebergegasan.
Esai-esai dalam buku yang disunting khusus oleh Nirwan Ahmad
Arsuka ini bisa dibayangkan sebagai trilogi. Satuan pertama, tulisan dari pelaku
atau orang dalam yang diwakili oleh Yudi Ahmad Tajudin dan Gunawan Maryanto. Dalam
masing-masing esainya, mereka sama-sama mencatat rekam proses pertunjukan yang
mereka sutradarai. Yudi bicara tentang proses Tubuh Ketiga dan Gunawan mencatat perjalanan Repertoar Hujan. Sudut pandang ini memang sangat dibutuhkan, ketika
literatur Teater Indonesia kekurangan catatan proses dari seorang pelaku. Tetapi,
seturut-sepandang dengan beberapa pengamat yang disampaikan pada peluncuran
buku ini beberapa waktu yang lalu (31-01-2015) di Yogyakarta, saya juga
menyayangkan sebab buku ini tidak menyertai catatan proses dari seorang aktor.
Catatan mereka penting dihadirkan, sebab paling tidak, publik mengetahui
bagaimana seorang aktor bergelut dengan dirinya dan dengan tokoh yang
diperankannya. Dalam tulisan itu, baik Yudi mau pun Gunawan sama-sama bertindak
sebagai sutradara. Di luar yang dianggap kurang itu, catatan mereka cukup
representatif untuk mengetahui dinamika proses: bagaimana Teater Garasi
memproduksi dan memaknai karya-karyanya.
Pengamatan
dari seorang pengamat-penonton merupakan satuan kedua yang diundang khusus
untuk kepentingan pembekuan dalam esai ini. Tulisan mereka menjadi penting
karena situasi ‘keberjarakan’. Mereka melihat hal-hal yang barangkali terlewat,
sekaligus kritik terhadap hal-hal yang belum dan telah dicapai, serta yang semestinya
dilakukan Teater Garasi, semisal kritik dari Nirwan Dewanto (Dua Belas Fragmen. Hal. 140). Baginya,
pertunjukan-pertunjukan Teater Garasi seperti parade kepintaran atau karnaval pustaka.
Teater Garasi ternyata juga terjangkit teater heroisme jenis kelima yang
berwujud intelektualisme. Purnanya, kepintaran harus selesai ketika sudah
sampai panggung. Kritik yang menyenangkan ini sekaligus melemahkan pernyataan gegabah
Alia Swastika (Teater Garasi Dua
Dasawarsa: Pandangan Politik Kaum Muda. Hal. 36), bahwa Teater Garasi—mengingat
sumbangan kelompok ini dalam pertumbuhan seni pertunjukan di Indonesia—telah
menjadi semacam ‘kanon’, sebuah pengakuan yang entah disambut atau diabaikan
oleh Teater Garasi sendiri. Sementara esai yang masing-masing ditulis oleh
Barbara Hatley, Wicaksono Adi, Afrizal Malna, Farah Wardani, Jennifer Lindsay,
Yoshi Fajar Kresno Murti, Marco Kusumawijaya dan Goenawan Mohamad adalah pengkayaan
wacana dan sudut pandang yang dimunculkan dari seorang pengamat-penonton. Tulisan-tulisan
mereka adalah diskusi yang membahagiakan.
Sedangkan
tulisan Intan Paramaditha (Goyang
Penasaran: Catatan dan Perjalanan) dan Landung Simatupang (Teater Garasi, Sekelumit Catatan dari
Keterlibatan Saya) termasuk dalam satuan ketiga, yaitu keterlibatan.
Keterlibatan mereka dalam salah satu nomor pertunjukan Teater Garasi perlu
diperhatikan dalam sudut pandang tersendiri. Catatan mereka menjadi unik,
ketika melakukan kerja bersama dengan kelompok yang mengikat dirinya dalam satu
unit kolektif seniman lintas disiplin yang diposisikan sebagai suatu perjumpaan
antara yang dari dalam dan dari luar.
Cermin
20 tahun adalah cermin untuk melihat dirinya, menengok
kembali bentangan panjang: jelajah ide dan wacana, eksplorasi artistik dan
sikap berkesenian. Cermin bukan sekadar penghadiran nostalgia atas capaian, tetapi
juga upaya memeriksa kembali dirinya dan mengidentifikasi sesuatu yang belum
dan seharusnya dikerjakan. Cermin sebagai sikap untuk terus belajar.
Dua buku ini bak pengantin di depan cermin, dan perlu
diduduk-sandingkan dalam pengkayaan daftar pustaka seni pertunjukan kita.